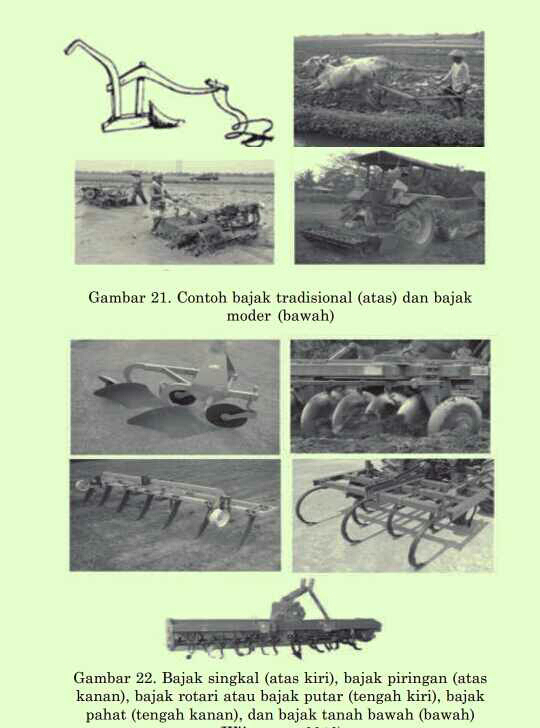Rabu, 19 Juli 2023
agronomi 1
By tewasx.blogspot.com at Juli 19, 2023
agronomi 1
Pertumbuhan (growth) adalah proses pertambahan
ukuran sel atau organisme tanaman (bersifat kuantitatif/
terukur) yang tidak dapat balik (irreversible) berupa
pertambahan protoplasma (jumlah dan isi sel) akibat
pertambahan ukuran dan jumlah sel yang dicerminkan
adanya penambahan bobot kering (ada penambahan volume,
massa, tinggi, atau ukuran lainnya). Dapat pula diartikan
sebagai perubahan secara kuantitatif selama siklus hidup
tanaman yang bersifat tak terbalikkan berupa bertambah
besar ataupun bertambah beratnya tanaman atau bagian
tanaman akibat adanya penambahan unsur-unsur struktural
yang baru. Peningkatan ukuran tanaman yang tidak balik
pada pertumbuhan sebagai akibat dari pembelahan dan
pembesaran sel. Sedangkan perkembangan (development)
diartikan sebagai proses perubahan secara kualitatif atau
mengikuti pertumbuhan tanaman/bagian-bagiannya karena
adanya diferensiasi (perubahan morfologis dan fungsi), suatu
perubahan dalam tingkat lebih tinggi/kompleks. Misalnya,
perubahan dari tahap vegetatif ke generatif atau perubahan
dari benih-kecambah-tanaman muda-tanaman dewasa4.1. Dasar-Dasar Pertumbuhan Tanaman di Dalam Sel
Pertumbuhan tanaman (growth) ditunjukkan oleh
pertambahan ukuran dan berat kering yang tidak dapat
balik. Pertambahan ukuran dan berat kering suatu
organisme mencerminkan pertambahan protoplasma,
yang mungkin terjadi karena baik ukuran sel maupun jumlah
selnya bertambah (Harjadi, 1996). Pertambahan ukuran sel
mempunyai batas karena berkaitan dengan hubungan antara
volume dengan luas permukaan.
Pertambahan protoplasma berlangsung melalui suatu
rentetan persitiwa dimana air (H2O), karbondioksida (CO2
),
dan garam-garam anorganik diubah menjadi bahan-bahan
hidup (karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain). Dalam
kaitannya dengan sel-sel tanaman, persitiwa tersebut
mencakup pembentukan karbohidrat melalui proses
fotosintesis, pengisapan dan gerakan air dan unsur hara
melalui proses absorpsi dan translokasi, penyusunan dan
prombakan protein dan lemak dari fragmen carbon
(karbohiodrat) dan persenyawaan anorganik melalui proses
metabolisme, dan perombakan bahan-bahan hidup,
terutama karbohidrat, untuk mendapatkan tenaga/energi
kimia melalui proses respirasi. Proses-proses tersebut
saling berhubungan satu dengan yang lain, yang merupakan
dasar-dasar pertumbuhan tanaman di dalam sel.
Fotosintesis merupakan cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi. Fotosintesis adalah
pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu
proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar
matahari. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya
cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Dengan kata
lain, fotosintesis merupakan proses penyusunan bahan
organik (gula/karbohidrat) dari H2O dan CO2 dengan bantuan
energi cahaya. Fotosintesis hanya akan terjadi jika tumbuhan
mempunyai pigmen fotosintesis, yaitu pigmen yang berfungsi
sebagai penangkap energi cahaya matahari lalumengkonversikannya menjadi energi kimia yang terikat
dalam molekul karbohidrat. Secara sederhana, reaksi
fotosintesis adalah seperti gambar di bawah ini:
Selain gula (karbohidrat), pada proses fotosintesis juga
di hasilkan oksigen dan air. Itu sebabnya tumbuhan hijau
dikatakan sebagai produsen oksigen bagi dunia sehingga
sangat efektif untuk menanggulagi polusi udara dan efek
rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.
Pada reaksi proses fotosintesis di atas, dapat dilihat
bahwa fotosintesis membutuhkan dua komponen utama,
yaitu klorofil (zat hijau daun) dan cahaya matahari (energi
matahari). Karena itu proses fotosintesis mutlak
membutuhkan cahaya dan hanya dapat terjadi pada
tumbuhan yang memiliki pigmen fotosintesis, yang dalam
bahasa sederhana disebut klorofil. Fungsi klorofil adalah
untuk menyerap sinar matahari sehingga di sebut juga
sebagai pigmen fotosintesis. Klorofil terdapat dalam
organel yang disebut kloroplas. Oleh karena itu, proses
fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi
hanya pada sel yang memiliki kloroplast dan mengandung
pigmen fotosintesis. Sel yang tidak mempunyai pigmen
fotosintetis tidak mampu melakukan proses
fotosintesis. Meskipun hampir seluruh bagian tubuh
tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas,
namun sebagian besar energi dihasilkan di daun.
Selain klorofil, tumbuhan juga mempunyai pigmen lain
yaitu antosianin dan karotenoid. Karotenoid sendiri
terdiri atas karoten dan xantofil. Seperti pigmen lainnya,
klorofil hanya dapat menyerap sebagian cahaya tampak.
Klorofil dapat menyerap cahaya merah dan biru sangat baik,
sedangkan cahaya hijau sangat sedikit diserap. Oleh karena
itulah, tumbuhan yang mengandung klorofil terlihat
berwarna hijau oleh mata kita karena cahaya hijau lebih
banyak dipantulkan. Karoten adalah pigmen yang
menyebabkan warna oranye, xantofil sebagai pigmen yangmenyebabkan warna kuning, sedangkan antosianin adalah
pigmen yang memberikan warna biru, ungu, violet, dan
merah. Adanyya pigmen warna oranye, kuning, biru, merah,
dan ungu ini menyebabkan daun memiliki warna beraneka
ragam. Terdapat beberapa jenis klorofil, yaitu klorofil a, b,
c, dan d. Klorofil a merupakan jenis klorofil yang paling
penting dalam fotosintesis. Klorofil a dapat menyerap cahaya
maksimal pada panjang gelombang 430 nm dan 662 nm,
sedangkan klorofil b yang juga berperan dalam fotosintesis
menyerap cahaya pada 453 dan 642 nm.
Berdasarkan proses reaksinya, rentetan dari reaksi
fotosintesis dapat digolongkan menjadi 2 tahap reaksi yaitu
reaksi terang (reaksi yang memerlukan cahaya) dan reaksi
gelap (reaksi yang tidak memerlukan cahaya).
Reaksi terang yaitu reaksi fotosintesis dimana klorofil
menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi
kimia dalam bentuk ATP, dan pada saat bersamaan terjadi
pemecahan molekul air (H2O) menjadi hidrogen dan oksigen,
yang disebut dengan fotolisis. Reaksi terang secara
sederhana seperti berikut:
Oksigen dilepaskan sebagai melokel O2
dalam bentuk
gas dan hidrogen (H+
) ditangkap oleh penerima hydrogen
yaitu nikotinamid-adenin-dinukleotida-fosfat (NADP+
)
menjadi molekul NADPH. Langkah ini disebut reaksi Hill
(NADP telah bertindak sebagai pereaksi Hill). Penangkapan
energi cahaya dengan pengubahan adenosine-difosfat (ADP)
menjadi adenosine-trifosfat (ATP) disebut reaksi
fotofosforilasi (penambahan fosfat ke ADP menjadi ATP
dalam keadaan ada cahaya). Gabungan dari reaksi Hill dan
fotofosforilasi dikenal dengan reaksi terang dalam proses
fotosintesis.
Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak
membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses
reduksi/konversi CO2 menjadi gula/karbohidrat. Secara
sederhana persamaan reaksi pada reaksi gelap dalam
fotosintesis seperti berikut:
Dalam reaksi gelap, energi yang dihasilkan (NADPH dan
ATP) dalam reaksi terang dipakai mensintesis gula dari CO2.
Reaksi penyusunan tersebut tidak lagi langsung bergantung
pada keberadaan cahaya, walaupun prosesnya berlangsung
bersamaan dengan proses reaksi cahaya. Reaksi gelap dapat
terjadi karena adanya enzim fotosintesis. Sesuai dengan
nama penemunya, yaitu Benson dan Calvin, daur reaksi
penyusunan zat gula itu di sebut daur Benson-Calvin. Reaksi
gelap berlangsung di dalam stroma kloroplas, serta
mengkonversi CO2
untuk gula. Reaksi ini tidak
membutuhkan cahaya secara langsung, tetapi itu sangat
membutuhkan produk-produk dari reaksi terang (ATP dan
bahan kimia lain yang disebut NADPH).
Respirasi (pernapasan) pada tumbuhan adalah proses
untuk memperoleh energi dengan merombak bahan-bagan
organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis,
sehingga dalam pengertian dangkal/sederhana, respirasi
adalah kebalikan dari proses fotosintesis, dengan persamaan
reaksi sebagai berikut.
Pada dasarnya respirasi adalah proses oksidasi molekul
gula atau asam-asam lemak dengan bantuan enzim untuk
meghasilkan energi. Energi yang dilepas melalui respirasi
ditangkap oleh ADP atau NADP membentuk energi kimia
dalam bentuk ATP atau NADPH. Artinya, energi kimia yang
ditangkap pada proses fotosintesis, dilepaskan lagi dengan
oksidasi senyawa-senyawa gula dan lemak yang dihasilkan
dalam proses fotosintesis. Energi kimia yang dihasilkan
dalam proses respirasi digunakan untuk mensintesis bahanbahan organik untuk kebutuhan pertumbuhan dan
perkembangan tanaman. Respirasi merupakan ciridari semua tanaman hidup, sehingga pengukuran dari
jumlah atau konsentrasi karbondioksida (CO2
) yang
dihasilkan dalam respirasi, merupakan salah satu variabel
untuk mengukur dan menguji suatu kehidupan.
Dari bermacam-macam bahan yang dihasilkan tanaman
dalam hidupnya, seperti karbohidrat, protein, lemak, sterol,
alkaloid, pigmen, dan lain-lain, semuanya berasal dari
pecahan-pecahan karbon (C) yang terbentuk melalui proses
fotosintesis dan dari hara anorganik yang diabsorpsi/diserap
dari tanah. Sintesis dari bahan-bahan tersebut (proses
anabolisme) dan perombakannya (proses katabolisme)
disebut dengan metabolisme. Proses pembentukan gula
dan bahan-bahan lain melalui penangkapan energi cahaya
dalam proses fotosintesis serta perombakan gula dan lemak
dan bahan-bahan lain dengan pelepasan energi dalam
respirasi, dapat dipandang sebagai peristiwa metaiolisme
anabolik dan katabolik yang khas dalam tumbuhan.
Absorpsi hara adalah penyerapan unsur hara dari tanah
oleh tanaman untuk disintesis menjadi bahan organik.
Absorpsi hara terjadi karena tumbuhan merupakan makhluk
hidup yang tergantung sepenuhnya pada bahan anorganik
dari lingkungannya. Tumbuhan memerlukan cahaya
matahari sebagai sumber energi untuk melakukan
fotosintesis. Untuk mensintesis bahan organik, tumbuhan
memerlukan bahan mentah dalam bentuk bahan-bahan
anorganik seperti karbon dioksida, air, dan berbagai mineral
yang ada sebagai ion anorganik dalam tanah. Melalui sistem
akar dan sistem tunas yang saling berhubungan, tumbuhan
memiliki keterkaitan yang sangat intensif dengan
lingkungannya seperti tanah dan udara yang menyediakan
bahan anorganik untuk membentuk senyawa karbon
komplek seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain
sebagainya .
Tanah merupakan suatu sistem yang kompleks, berperan
sebagai sumber unsur hara dan air bagi tanaman.
Penyerapan unsur hara oleh tanaman dari dalam tanah umum
melalui tiga mekanisme, yaitu aliran massa (mass flow),
difusi (diffusion), dan intersepsi akar (root interception).
Penyerapan hara melalui aliran massa adalah suatu
mekanisme gerakan unsur hara dari tanah menuju ke
permukaan akar bersama-sama dengan gerakan massa air
karena dipacu oleh adanya transpirasi. Selama proses
transpirasi tanaman berlangsung, terjadi juga proses
penyerapan air oleh akar tanaman melalui aliran massa.
Bersamaan dengan pergerakan massa air ke akar dan daun
karena adanya transpirasi, ikut juga terbawa unsur hara
yang terkandung dalam air tersebut. Peristiwa tersedianya
unsur hara yang terbawa bersamaan dengan gerakan massa
air ke permukaan akar tanaman dikenal dengan aliran
massa. Terserapnya air karena adanya perbedaan potensial
air yang disebabkan oleh proses transpirasi tersebut, dimana
air bergerak dari potensial tinggi ke rendah. Nilai potensial
air di dalam tanah lebih tinggi dibandingkan dengan
permukaan bulu akar sehingga air tanah masuk kedalam
jaringan akar, kemudian potensial air di daun lebih rendah
dari di akar sehingga air bersama hara mengalir ke daun.
Ketersediaan unsur hara ke permukaan akar tanaman,
dapat juga terjadi karena melalui mekanisme perbedaan
konsentrasi. Pergerakan hara dari konsentrasi tinggi ke
konsentrasi lebih rendah melewati membran semipermeabel
dalam sel hidup dikenal dengan difusi. Dalam hal ini sel
bertindak sebagai pompa metabolik dengan memerlukan
energi (bahan bakar) yang disuplai dari proses respirasi,
sehingga disebut dengan istilah pengambilan aktif (active
uptake).
Penyerapan melalui intersepsi akar adalah karena
pertumbuhan akar tanaman yang memperpendek jarak
dengan keberadaan unsur hara, dengan kata lain akar
tanaman tumbuh dan memanjang, sehingga memperluas
jangkauan akar tersebut. Perpanjangan akar menjadikan
permukaan akar lebih mendekati posisi keberadaan unsur
hara, baik unsur hara yang ada dalam larutan tanah,
permukaan koloid liat, maupun permukaan koloid organik.
Mekanisme intersepsi akar sangat berbeda dengan kedua
mekanisme sebelumnya, yaitu aliran massa dan difusi. Padaaliran massa dan difusi terjadi pergerakan unsur hara
menuju ke akar tanaman, sedangkan pada intersepsi akar,
terjadi gerakan atau perpanjangan akar yang memperpendek
jarak dengan keberadaan unsur hara sehingga hara bisa
absorpsi.
Translokasi pada tanaman berkaitan dengan gerakan
atau transportasi zat-zat organik dan anorganik yang
terlarut dari satu bagian tanaman ke bagian lainnya. Dalam
proses transportasi tersebut, terjadi pembagian air, unsur
hara atau hara mineral dan hasil fotosintesis kepada
jaringan-jaringan tanaman yang membutuhkan. Persitiwa
pembagian tersebut disebut dengan translokasi. Terdapat
dua jenis translokasi yang utama dalam tanaman yaitu
tranlokasi melalui xylem dan melalui floem. Translokasi hara
dan air terutama berlangsung melalui xylem dari akar ke
daun (tajuk), sedangkan translokasi hasil fotosintesis
(fotosintat) berlangsung melalui floem dari daun ke seluruh
tubuh tanaman. Terdapat perbedaan prinsip antara
pengangkutan lewat xylem dan floem. Pada pengangkutan
lewat xylem, pengangkutan berlangsung melalui sel-sel mati,
yang ditransportasikan adalah hara dan air, serta
pergerakannya searah yaitu dari bawah ke atas (dari akar
ke tajuk). Sedangkan pada pengangkutan lewat floem,
pengangkutan berlangsung melalui sel-sel hidup, yang
ditransportasikan adalah hasil fotosintat dan senyawasenyawa organik lainnya, dan pergerakannya dua arah, bisa
dari atas ke bawah (dari daun ke bagian-bagian lainnya di
bagian bawah) atau dari bawah ke atas (dari daun ke bagianbagian lainnya yang lebih di atas).
Pada transportasi melalui xylem, pengangkutan dimulai
setelah air dan hara masuk dari larutan tanah ke akar. Air
dan unsur hara masuk melalui rambut akar melewati selsel akar sampai di bagian tengah akar. Perjalanan air dan
hara ini terjadi di luar pembuluh sehingga hal ini dinamakan
pengangkutan ekstravaskuler. Setelah itu, air dan hara
menyebrang masuk ke pembuluh xylem akar, selanjutnya
diteruskan pengangkutannya ke xylem batang menuju ke
daun. Akar, batang dan daun didalamnya terdapat
pembuluh-pembuluh xilem yang tergabung di dalam berkaspengangkut dan pembuluh-pembuluh itu sambung
menyambung membentuk satu rangkaian sampai menuju ke
daun. Berbeda dengan pengangkutan ekstravaskuler,
pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan air dan
zat terlarut yang terjadi dalam berkas pembuluh xilem dan
floem secara vertikal. Vertikal maksudnya adalah
pengangkutan air dan unsur hara oleh xilem dari akar
menuju daun. Sebaliknya, pengangkutan zat makanan
(fotosintat) dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan dilakukan
oleh floem.
Pengangkutan air dan hara berlangsung karena beberapa
faktor seperti karena adanya daya isap daun dan kapilaritas
pembuluh. Daya isap daun terjadi karean dipicu oleh adanya
transpirasi. Hilangnya air melalui penguapan pada daun
mengakibatkan perbedaan kadar cairan sel-sel di permukaan
daun dengan sel-sel yang lebih di dalam. Kekurangan cairan
di sel-sel permukaan daun ini diambilkan dari sel-sel
dibawahnya, lalu dari pembuluh xilem daun dan trakhir dari
pembnuluh xylem akar. Pembuluh xilem daun berhubungan
dengan pembuluh xilem batang, demikian pula pembuluh
xilem batang berhubungan dengan pembuluh xilem akar.
Dengan adanya hubungan pembuluh tersebut terjadi aliran
air dan hara dari akar ke permukaan daun yang airnya
menguap karena transpirasi. Karena daunlah yang seolaholah mengisap air dari akar mencapai daun maka daya
tersebut dinamakan daya isap daun. Daya isap daun ini
berkaitan pula dengan prinsip fisika kapilaritas pembuluh,
dimana air dalam pembuluh xylem melekat pada dinding
pembuluh, sehingga permukaan air naik lebih tinggi dan hal
itu membantu pengangkutan air dari pembuluh xylem akar
ke pembuluh xylem daun lebih mudah.
Pada pengangkutan lewat floem, terjadi pemuatan
(loading) hasil fotosintat dari sel-sel daun yang berfosintesis
ke pembuluh floem daun terdekat, kemudian dari sana
diangkut ke seluruh bagian tanaman. Fungsi floem adalah
sebagai pembuluh yang mentranslokasikan bahan organik
yang terutama berisi karbohidrat hasil fotosintesis.
Fotosintat yang dihasilkan pada daun dan sel-sel fotosintetik
lainnya harus diangkut ke organ atau jaringan lain agardapat dimanfaatkan oleh pertumbuhan atau ditimbun
sebagai bahan cadangan. Sesungguhnya yang diangkut
melalui floem tidak hnaya senyawa hasil fotosintesis, tetapi
juga senyawa organik lainnya dan beberapa senyawa
anorganik seperti hara mineral yang diremobilisasi dari
daun ke bagian lain yang lebih membutuhkan.
Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume
yang irreversible (tidak dapat balik) karena adanya
pembesaran sel dan pertambahan jumlah sel atau
pembelahan sel (pembelahan mitosis) atau keduanya.
Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dinyatakan
secara kuantitatif karena pertumbuhan dapat diketahui
dengan mengukur besar dan tinggi batang, menimbang
massa sel baik berupa berat kering maupun berat basahnya,
menghitung jumlah daun, jumlah bunga, jumlah buah, dan
lain sebagainya.
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman melibatkan
tiga proses penting yaitu pembelahan sel (cellular division),
pembesaran sel (enlargement) dan diferensiasi
(differentiation). Pembelahan dan pembesaran sel
merupakan proses yang saling berkaitan. Pembesaran sel
sering diawali karena adanya pembelahan sel, seperti terjadi
pada sel maristematik, walaupun sebenarnya kedua proses
tersebut dikendalikan oleh hal yang berbeda. Pembesaran
tidak menginduksi pembelahan sel dan pembelahan sel
tidak selalu mendahului terjadinya pembesaran sel.
Contohnya, pembesaran sel dapat terjadi karena masuknya
air ke dalam sel. Mula-mula dinding sel yang kaku (rigid)
bertambah longgar (loosening) karena adanya asam-asam
organik yang disekresikan ke dinding sel yang dipengaruhi
oleh hormon auksin. Dinding sel yang bertambah longgar
menyebabkan air dapat masuk ke dalam sel tersebut melalui
proses osmosis sehingga terjadi pembesaran sel. Jadi air
dan hormon auksin berperan sangat penting dalam
pembesaran sel. Sedangkan diferensiasi adalah suatu situasi
dimana sel-sel meristematik berkembang menjadi dua atau
lebih macam sel/jaringan/organ tanaman yang secara
kualitatif berbeda satu dengan yang lainnya. Diferensiasi
merupakan proses hidup yang menyangkut transformasi sel
tertentu ke sel-sel yang lain menurut spesialisasinya (baik
spesialisasi dalam hal proses biokimia, fisiologi, maupun
struktural). Misalnya, pembentukan jaringan xilem dan
floem. Jadi, diferensiasi merupakan perubahan yang terjadi
dari keadaan sejumlah sel, membentuk organ-organ yang
mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda.
Pertumbuhan menyebabkan meningkatnya berat kering
tanaman karena tanaman aktif berfotosintesis. Oleh karena
itu kecepatan pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor
lingkungan, proses fisiologi dan genetik tanaman.
Pertumbuhan tanaman terjadi pada sel dan atau jaringan
meristem yang masih aktif. Secara umum pertumbuhan
diawali oleh stadium zigot yang merupakan hasil
pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Pembelahan
zigot menghasilkan jaringan meristem yang akan terus
membelah dan mengalami diferensiasi. Adapun letak
pertumbuhan tanaman (letak jaringan meristem) adalah
pada:
a. Ujung suatu organ (meristem apical). Meristem apikal
biasanya tetap bersifat embrionik dan mampu tumbuh
dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga disebut juga
indeterminate meristem. Misalnya pada ujung batang
dan ujung akar.
b. Meristem lateral yaitu meristem yang berkaitan dengan
pertumbuhan membesar. Misalnya pada jaringan
cambium.
c. Meristem intercalar yaitu meristem yang terletak antara
daerah-daerah jaringan yang telah terdiferensiasi.
Meristem seperti ini kebanyakan terdapat pada familia
Gramineae. Pada organ-organ tumbuhan lain, misalnya
bunga, akar, buah, pola pertumbuhannya agak berbeda
dengan batang dan hanya bersifat embrionik dalam
jangka waktu tertentu, sehingga disebut determinate
meristem
Pertumbuhan tanaman dapat dibedakan menjadi dua
macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan
sekunder. Pertumbuhan primer pada tumbuhan adalah
pertumbuhan yang terjadi mulai dari tahap embrio hingga
dewasa. Pertumbuhan primer menghasilkan pemanjangan
akar dan batang. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil
pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Berlangsung
pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar
dan batang. Embrio memiliki 3 bagian penting, yakni: a.
tunas embrionik yaitu calon batang dan daun, b. akar
embrionik yaitu calon akar, dan c. kotiledon yaitu cadangan
makanan. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang
berdasar aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yakni: a.
daerah pembelahan, sel-sel di daerah ini aktif membelah
(meristematik), b. daerah pemanjangan, berada di belakang
daerah pembelahan, dan c. daerah diferensiasi, bagian paling
belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel yang
mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya
serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang.
Jadi, pertumbuhan primer terjadi karena adanya proses
aktivitas sel atau jaringan meristem primer yang terdapat
pada daerah titik tumbuh yang utama, yaitu pada bagian
ujung batang dan ujung akar tanaman
Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan primer adalah
terbentuknya embrio, tumbuhnya akar dari ujung akar,
tumbuhnya batang dari ujung batang, dan pertumbuhan
primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang.
Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan yang
memiliki kambium. Pertumbuhan sekunder menyebabkan
batang dan akar bertambah lebar. Pertumbuhan sekunder
merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder yaitu
kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai
pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae dan menyebabkan
membesarnya ukuran (diameter) tumbuhan. Pada monokotil,
tidak terdapat kambium. Karenanya, tidak ada pertumbuhan
sekunder.
Gambar 11. Pertumbuhan primer pada ujung pucuk dan
ujung akar dan pertumbuhan sekuner pada cambium
(sumber: https://www.google.co.id/pertumbuhan+primer+
dan +sekunder+ tanaman, diakses pada 26 Desember 2017)
Mula-mula kambium hanya terdapat pada ikatan
pembuluh, yang disebut kambium vasis atau kambium
intravaskuler. Fungsinya adalah membentuk xilem dan floem
primer. Selanjutnya parenkim akar/batang yang terletak di
antara ikatan pembuluh, menjadi kambium yang
disebut kambium intervasis. Kambium intravasis dan
intervasis membentuk lingkaran tahun berbentuk
konsentris. Kambium yang berada di sebelah dalam jaringan
kulit berfungsi sebagai pelindung, terbentuk akibat
ketidakseimbangan antara permbentukan xilem dan floem
yang lebih cepat dari pertumbuhan kulit. Jadi, pertumbuhan
sekunder adalah pertambahan diameter batang atau cabang
karena aktifitas kambium yang mebentuk xylem dan floem
sekunder (Gambar 12 dan 13).
Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan
kualitatif (bentuk dan sifat) organisme atau bagiannya yang
melibatkan perubahan struktur serta fungsi yang lebih
kompleks. Siklus teratur dari perkembangan tanaman dalam
hidupnya menyangkut pola perubahan yang kompleks dalam
sel dan jaringan. Siklus tersebut mulai dari perkecambahan
biji kemudian menjadi masa muda (juvenile), dewasa (adult),
berbunga (flowering), dan berbuah (fruitting). Pada tanaman
tahunan , tanaman siap kembali ke siklus muda dengan
menumbuhkan tunas baru setelah periode diam beberapa
saat (dormancy) kemudian berbunga dan berbuah kembali
(demikain seterusnya), sedangkan pada tanaman setahun
dan dwitahunan pembuahan dan terbentuknya biji
merupakan tanda bagi tanaman tersebut untuk memasuki
tahap akhir dari pertumbuhan tanaman, yaitu penuaan
(senescence) dan kematian.Pertumbuhan dan perkembangan merupakan gejalagejala yang saling berhubungan. Pertumbuhan seperti telah
dijelaskan di atas adalah pertambahan ukuran (dan biasanya
dalam berat kering) yang tidak dapat balik (irreversible).
Sedangkan perkembangan (development) merupakan suatu
kombinasi dari sejumlah proses yang kompleks yaitu proses
diferensiasi, dan ditunjukkan oleh perubahan-perubahan
yang lebih kompleks menyangkut spesialisasi secara anatomi
dan fisiologi.
Perkembangan tanaman erat kaitannya dangan
pembentukan organ-organ tumbuhan dan perubahan bentuk
dari embrio atau biji hingga menjadi tumbuhan utuh. Hal
penting yang harus dipahami dalam perkembangan adalah
adanya diferensiasi sel. Organ tumbuhan seperti akar,
batang, dan daun, semuanya tersusun atas berbagai jaringan.
Perlu diketahui bahwa semua jaringan pada tumbuhan
berasal dari satu jaringan, yaitu jaringan meristem, dan
pada perkembangan tumbuhan terdapat mekanisme yang
menyebabkan sel-sel muda (meristem) berkembang menjadi
bermacam-macam sel atau jaringan dewasa. Mekanisme
tersebut disebut diferensiasi.
Diferensiasi ditunjukkan oleh perubahan yang lebih
tinggi (meristem menjadi kotiledon, lalu menjadi bakal daun,
dan seterusnya) sehingga terjadi spesialisasi secara
anatomis dan fisiologis. Diferensiasi ditentukan oleh peran
gen tertentu dalam sel termasuk keterlibatan fitohormon.
Proses diferensiasi mempunyai tiga syarat, yaitu:(1) hasil
asimilasi yang tersedia dalam keadaan berlebihan untuk
dapat dimanfaatkan pada kebanyakan kegiatan metabolisme,
(2) temperatur yang menguntungkan, dan (3) terdapat sistem
enzim yang tepat untuk memperantarai proses diferensiasi.
Diferensiasi adalah proses teratur yang menyebabkan
sel dengan struktur dan fungsi sama menjadi berbeda. Hal
tersebut terjadi selama hidup tumbuhan dan selalu diikuti
oleh perubahan fisiologis yang kompleks. Diferensiasi
menghasilkan sel, jaringan, dan organ terspesialisasi untuk
fungsi yang berbeda. Contohnya, pada diferensiasi
pembentukan bunga, struktur sel dan tempat awal
tumbuhnya bunga bisa jadi sama dengan awal mulatumbuhnya tunas pucuk, tetapi karena proses diferensianya
berbeda maka yang tumbuh adalah bunga, bukan tunas
vegetatif (Sudjino, 2009).
Pada proses diferensiasi, dapat terjadi dua hal penting
yaitu perubahan struktural yang akan mengarah pada
pembentukan organ dan perubahan kimiawi untuk
meningkatkan kemampuan sel. Sebagai contoh, luka pada
tumbuhan dapat merusak pola struktural tumbuhan
tersebut, misalnya karena dimakan oleh herbivora atau
karena luka mekanis maka sel dan jaringan pengangkut di
batang atau cabang tersebut rusak. Karena terjadi luka, selsel dekat daerah luka merespons adanya kerusakan dengan
melakukan dediferensiasi sehingga sel-sel yang rusak
tersebut kembali menjadi bersifat meristematik dengan
memprogram ulang gen-gennya untuk melakukan
diferensiasi. Contoh lain, putusnya seludang pembuluh
menginduksi pembelahan sel-sel parenkim di sekitar luka.
Hal tersebut membentuk lapisan yang menghubungkan
ujung-ujung ikatan pembuluh yang rusak dan lapisan
jaringan parenkim itu kemudian berdediferensiasi menjadi
jaringan pembuluh yang menghubungkan jaringan pembuluh
dan menutup luka. Karena adanya mekanisme dediferensiasi
ini, maka perkembangan tanaman dapat dikatakan bersifat
dapat terbalikkan (reversibel), berbeda dengan pertumbuhan
yang bersifat tidak dapat balik (irreversible).
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman berjalan
secara simultan/bersamaan. Selama pertumbuhannya,
tanaman mengalami proses diferensiasi, pematangan
organ, dan peningkatan menuju kedewasaan. Pada saat
itulah, tumbuhan mengalami proses yang disebut
perkembangan. Serangkaian proses perubahan bentuk
tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan
ini disebut juga morfogenesis. Dari hasil perkembangan,
tanaman menjadi semakin dewasa dan lengkap organnya.
Proses pembentukan organ tersebut disebut sebagai
organogenesis, yang merupakan bagian dari proses
perkembangan atau morfogenesis. Perkembangan tidak
dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi dilihat dengan
adanya peningkatan menuju pada kesempurnaan (kualitatif)Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman
merupakan hasil kerja sama antara faktor dalam (internal)
dan faktor luar (eksternal). Salah satu faktor internal yang
penting mempengaruhi perumbuhan dan perkembangan
tanaman adalah hormon tumbuh atau zat pengatur
pertumbuhan. Hormon tumbuh merupakan zat spesiûk
berupa zat organik yang dihasilkan oleh suatu bagian
tumbuhan, dalam konsentrasi rendah tertentu dapat
mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Adanya hormon tertentu pada tumbuhan akan menyebabkan
pertumbuhan dan perkembangan berlangsung lebih cepat,
atau bila diperlukan secara alami tanaman bisa mengatur
pertumbuhannya agar menjadi lebih lambat. Hal tersebut
dimungkinkan karena tanaman secara internal memiliki
hormon tumbuh (endogenous hormone) yang dapat memacu
pertumbuhan (hormon promotor) seperti auksin, giberelin
dan sitokinin, serta hormon tumbuh yang menghambat
pertumbuhan (hormon inhibitor) seperti etilen dan asam
absisat/ABA. Bila dianalogkan dengan mobil, hormon
promotor pada tumbuhan adalah sistem gas hyang berfungsi
mengatur agar pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat,
sebaliknya hormon inhibitornya adalah sistem rem yang
berfungsi memperlambat pertumbuhan atau perkembangan
tanaman.
tahap -tahap pertumbuhan dan perkembangan tanaman
terdiri dari dua tahap , yaitu tahap vegetatif dan tahap
produktif. tahap vegetatif dimulai sejak biji mulai
berkecambah, tumbuh menjadi bibit dan dicirikan oleh
pembentukan daun-daun yang pertama dan berlangsung
terus sampai masa berbunga dan atau berbuah yang pertama.
tahap reproduktif terjadi pada pembentukan dan
perkembangan kuncup-kuncup bunga, bunga, buah, dan biji
atau pada pembesaran dan pendewasaan struktur
penyimpanan makanan seperti akar berdaging dan batang
berdaging
tahap vegetatif terutama terjadi pada perkembangan akar,
daun dan batang baru. tahap ini berhubungan dengan 3 proses
penting; (1) pembelahan sel, (2) pemanjangan sel, dan (3)
tahap awal dari diferensiasi sel.
Pembelahan sel terjadi pada pembuatan sel-sel baru. Selsel baru ini memerlukan karbohidrat dalam jumlah yang
besar, karena dinding-dindingnya terbuat dari selulosa dan
protoplasmanya kebanyakan terbuat dari gula. Jadi, bila
faktor-faktor lain dalam keadaan favorabel, laju pembelahan
sel tergantung pada persediaan karbohidrat yang cukup.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, pembelahan sel terjadi
dalam jaringan-jaringan meristematik pada titik-titik
tumbuh batang dan ujung-ujung akar dan pada kambium.
Karena itu, jaringan-jaringan ini harus dilengkapi dengan
makanan yang cukup, hormon-hormon dan vitamin-vitamin
yang juga cukup jumlahnya dengan tujuan untuk membuat
sel-sel baru.
Pemanjangan sel terjadi pada pembesaran sel-sel baru.
Proses ini membutuhkan: (1) pemberian air yang banyak, (2)
adanya hormon tertentu yang memungkinkan dindingdinding sel merentang, dan (3) adanya gula. Daerah
pembesaran sel-sel berada tepat di belakang titik tumbuh.
Kalau sel-sel pada daerah ini membesar, vakuola-vakuola
yang besar terbentuk. Vakuola ini secara relatif mengisap
air dalam jumlah besar. Akibat dari absorpsi air ini dan
adanya hormon perentang sel, sel-sel menjadi memanjang.
Sebagai tambahan dari pertambahan besar sel, dindingdindingnya bertambah tebal, karena menumpuknya selulosa
tambahan yang terbuat dari gula.
Tahap awal dari diferensiasi sel atau pembentukan
jaringan terjadi pada perkembangan jaringan-jaringan
primer. Perkembangannya memerlukan karbohidrat,
seperti penebalan dinding dari sel-sel pelindung pada
epidermis batang dan perkembangan pembuluh-pembuluh
kayu, baik di batang maupun di akar. Jadi kalau suatu
tanaman membuat sel-sel baru, pemanjangan sel-sel tersebut
dan penebalan jaringan-jaringan sebenarnya merupakanproses mengembangkan batang, daun dan sistem
perakarannya. Kalau laju pembelahan sel dan
perpanjangannya serta pembentukan jaringan berjalan
cepat, pertumbuhan batang, daun dan akar juga berjalan
cepat. Sebaliknya, bila laju pembelahan sel lambat,
pertumbuhan batang, daun dan perakaran dengan sendirinya
lambat juga. Karena pembelahan, pembesaran dan
pembentukan jaringan memerlukan persediaan karbohidrat
dan karena karbohidrat dipergunakan dalam proses-proses
ini, perkembangan batang, daun dan akar memerlukan
pemakaian karbohidrat. Jadi dalam tahap vegetatif dari suatu
perkembangan, karbohidrat dipergunakan dan tanaman
menggunakan sebagian besar karbohidrat yang dibentuknya.
Dengan kata lain, tahap vegetatif merupakan tahap
penggunaan karbohidrat .
tahap reproduktif terjadi pada pembentukan dan
perkembangan kuncup-kuncup bunga, bunga, buah, dan biji
atau pada pembesaran dan pendewasaan struktur
penyimpanan makanan, akar-akar dan batang yang
berdaging. tahap ini berhubungan dengan beberapa proses
penting, yaitu: (1) pembuatan sel-sel yang relatif sedikit, (2)
pendewasaan jaringan-jaringan, (3) penebalan serabutserabut, (4) pembentukan hormon-hormon yang perlu untuk
perkembangan kuncup bunga (primordial), (5)
perkembangan kuncup bunga, bunga, buah, dan biji;
perkembangan alat-alat penyimpanan, dan (6) pembentukan
koloid-koloid hidrofilik (bahan yang dapat menahan air).
Untuk berlangsungunya tahap reproduksi ini membutuhkan
suplai karbohidrat, dalam kebanyakan hal karbohidrat ini
berupa pati dan gula. Dengan perkataan lain, bila suatu
tanaman mengembangkan bunga, buah dan biji atau alat
penyimpanan, tidaklah seluruh karbohidrat dipergunakan
untuk perkembangan batang, daun dan perakaran; sebagian
disisakan untuk perkembangan bunga, buah dan biji atau
alat-alat persediaan/penyimpanan lainnya. Sebagai contoh,
biji padi dan jagung, daging buah apel, umbi kentang dan
akar ubi jalar, batang tebu, semuanya berisi pati dan gula
dalam jumlah besar. Jadi pada tahap reproduktif dari
perkembangan tanaman, karbohidrat disimpan (ditimbun)
dan tanaman tersebut menyimpan sebagian besar
karbohidrat yang dibentuknya. Jadi tahap reproduktif
merupakan tahap penumpukan karbohidrat .
tahap vegetatif dan reproduktif dari perkembangan
tanaman dapat diumpamakan dengan suatu timbangan.
Tangan satu dari timbangan dapat diandaikan tahap vegetatif
yaitu perkembangan batang, daun, dan akar. Sedangkan
tangan satunya lagi dapat diandaikan sebagai tahap
reproduktif yaitu perkembangan bunga, buah dan biji, atau
alat-alat penyimpanan. , konsep ini
menyajikan tiga kemungkinan, yaitu:
a. tahap vegetatif mugkin dominan terhadap tahap
reproduktif, timbangan miring ke arah tahap vegetatif.
b. tahap reproduktif mungkin dominan terhadap tahap
vegetatif, timbangan miring ke arah tahap reproduktif.
c. Tak satu pun tahap yang dominan; kedua tangan
timbangan secara praktis sama tinggi (mendatar).
Namun jangan diartikan bahwa tahap vegetatif berjalan
tanpa tahap reproduktif ataupun bahwa tahap reproduktif
berjalan tanpa tahap vegetatif. Kalau tahap vegetatif dari suatu
tanaman sedang dominan, masih selalu ada sedikit tahap
reproduktif. Sebaliknya, kalau tahap reproduktif dominan,
masih selalu ada sedikit tahap vegetatif. Jadi, istilah
“timbangan” dipergunakan untuk menggambarkan tekanan,
atau yang dipentingkan dan bukannya kepada ada atau
tidaknya salah satu pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Kalau tahap vegetatif dari perkembangan tanaman
sedang dominan atas tahap reproduktifnya, penggunaan
karbohidrat dominan atas penumpukannya; lebih banyak
karbohidrat yang digunakan daripada yang disimpan. Kalau
tahap reproduktif dominan atas tahap vegetatifnya,
penumpukan karbohidrat dominan atas pemakaiannya; lebih
banyak karbohidrat yang disimpan daripada yang dipakai
Kalau tahap -tahap vegetatif dan reproduktif seimbang,
penggunaan dan penumpukan seimbang juga; secara praktis
karbohidrat yang dipakai dan disimpan sama banyaknya.
Sebagai contoh, ada tiga buah tanaman tomat (A, B dan
C) masing-masing sudah berumur 150 hari. Pada tanaman A
tahap vegetatifnya dominan terhadap tahap reproduktifnya;
pada tanaman B, tahap reproduktif dominan atas tahap
vegetatifnya; dan pada tanaman C kedua tahap berlangsung
bersamaan besarnya. Bagaimana wujud tanaman-tanaman
ini?. Tanaman A, akan sangat vegetatif, banyak terjadi
perkembangan batang, daun dan akar. Batangnya sukulen
(banyak mengandung air), daunnya lebar-lebar dengan
perkembangan kutikula yang sedikit. Pembungaan dan
pembuahan tidak akan terjadi ataupun tertekan, dindingdinding sel akan tipis-tipis, dan jaringan-jaringan penyokong
akan terbentuk dengan buruk. Dengan kata lain, kebanyakan
dari karbohidrat akan digunakan untuk perkembangan akar,
batang dan daun. Akibatnya, sedikit sekali karbohidrat yang
tersisa untuk perkembangan kuncup bunga, bunga, buah, dan
biji. Dalam hal ini, tahap vegetatif adalah dominan terhadap
tahap reproduktif dan penggunaan karbohidrat lebih banyak
daripada penumpukannya. Pertumbuhan bagian atas yang
berlebihan, bersamaan dengan kurangnya pertumbuhan
bunga, buah dan biji, biasanya terjadi dalam kondisi tanaman
dalam masa permulaan tumbuhnya. Tanaman mempunyai
laju fotosintesis yang cepat. Suhu menyokong pembelahan
sel yang cepat, dan air serta bahan-bahan esensial
berkecukupan. Sejumlah besar karbohidrat yang terbentuk,
bersenyawa dengan persenyawaan-persenyawaan nitrogen
untuk membentuk protoplasma yang dibentuk pada titiktitik tumbuh dari batang dan akar. Sebagai akibatnya prosesproses vegetatif dominan atas proses reproduktif. Tanaman
B akan mempunyai pertumbuhan vegetatif yang buruk dan
kerdil, akan membentuk beberapa buah. Sedikit
perkembangan daun dan batangnya. Batangnya akan
berkayu, ruas-ruasnya pendek, daun-daunnya agak sempit
dan berkutikula tebal. Bunga dan buah akan tampak,
dinding-dinding sel akan tebal, jaringan-jaringan pembuluh
akan dibentuk secara baik, dan jaringan-jaringan penyimpanakan penuh dengan pati. Karena batang sangat perlu untuk
mendukung bunga dan buah dan karena pada tanaman B
secara relatif mempunyai batang dan daun yang sedikit, hasil
panen akan sangat sedikit. Dalam hal ini, tahap reproduktif
dominan atas tahap vegetatifnya, dan penumpukan
kabohidrat dominan atas pemakaiannya. Tanaman-tanaman
yang lemah dan kerdil, biasanya akibat dari kondisi-kondisi
sebagai berikut: tanaman mempunyai laju fotosintesis yang
rendah atau agak rendah. Suhu atau persediaan air atau
suplai unsur-unsur esensial, atau beberapa faktor tertentu
yang lain, tidaklah favorable sekalipun untuk pembelahan
sel yang sedang-sedang cepatnya. Sebagai akibatnya,
karbohidrat menumpuk dan digunakan untuk proses
reproduktif lebih lanjut dari pada untuk keperluan proses
vegetatif. Tanaman C akan sedang-sedang pertumbuhan
vegetatifnya, dan akan banyak buahnya. Batangnya sedang
sukulennya, ruas sedang banyaknya, daun-daun sedang
luasnya dengan pembentukan kutikula yang normal.
Pembungaan dan pembuahan akan berlangsung bersamaan
dengan pembentukan batang, daun dan akar. Dinding sel
akan cukup tebalnya, dan pembentukan jaringan-jaringan
pembuluh akan normal. Dalam hal ini, jumlah karbohidrat
yang sedang-sedang digunakan untuk perkembangan bunga,
buah dan alat-alat cadangan makanan. Karena kedua tahap
vegetatif dan reproduktif tidaklah dominan, penggunaan dan
penumpukan karbohidrat tidak ada yang dominan dan
masing-masing tahap berlangsung secara bersamaan besarnya.
Pertumbuhan bagian atas yang sedang, bersama-sama dengan
perkembangan bunga, buah dan biji, biasanya berlangsung
pada kondisi-kondisi tanaman mempunyai laju fotosintesis
yang tinggi. Suhu dan keadaan lingkungan yang lainnya
menyokong pembelahan sel yang sedang-sedang
kecepatannya. Sebagai akibat tidak semua karbohidrat
digunakan untuk perkembangan batang dan daun; sebagian
disisakan untuk perkembangan bunga dan buah. Prosesproses vegetatif dan reproduktif tidak ada yang dominan,
dan tanamannya mempunyai pertumbuhan vegetatif yang
sedang dan berbuah banyak. Jadi pertumbuhan akar, batang
dan daun dihubungkan dengan penggunaan karbohidrat, danperkembangan bunga, buah dan biji atau sel-sel cadangan
dihubungkan dengan penumpukan karbohidrat (Tabel 6).
Dalam kaitan tersebut, maka: (1) yang berhubungan dengan
penggunaan karbohidrat adalah sukulensi yang berlebihan,
mudah patah (renyah atau getas), berair (juicy), beberapa
sifat yang sangat diinginkan pada suatu tanaman, untuk
sayuran dan buah, dan (2) yang berhubungan dengan
penumpukan karbohidrat adalah tidak “sukulen”, berkayu,
dan tahan terhadap kedinginan dan kepanasan atau
kekeringan, sifat-sifat yang sangat diinginkan pada tanaman
lain (tanaman-tanaman yang akan dipindahkan/
transplanting).
. Perimbangan tahap Reproduktif-Vegetatif dan
Tipe-tipe Pertumbuhan
Seperti diuraikan di atas, tahap vegetatif mungkin
dominan atas tahap reproduktif, atau tahap reproduktif
mungkin dominan atas tahap vegetatif atau tahap vegetatif dan
reproduktif tidak satupun yang nampak dominan. Beberapa
tanaman pertanian memerlukan suatu dominansi dari
proses-proses vegetatifnya sepanjang lingkungan hidupnya,dan yang lainnya memerlukan dominansi proses-proses
vegetatif selama bagian pertama dari lingkaran hidupnya
dan seimbang antara proses-proses vegetatif dan reproduktif
semasa akhir hidupnya. Pada umumnya, semua tanaman
memerlukan dominansi dari tahap -tahap vegetatif selama tahap
semai. Sesudah tahap ini, tanaman-tanaman dapat dibagi ke
dalam tiga kelompok yang sedikit banyak dapat dibedabedakan menjadi:
1. Tanaman-tanaman berbatang basah yang memerlukan
suatu dominansi dari tahap vegetatif selama tahap
pertama hidupnya, dan dominansi dari tahap reproduktif
selama masa akhir hidupnya, dimana yang pertama
kehilangan dominansinya secara berangsur-angsur
2. Tanaman berbatang basah yang tidak memerlukan
dominansi dari kedua tahap vegetatif maupun reproduktif.
Jadi keduanya harus seimbang
3. Tanaman berkayu yang memerlukan suatu dominansi
dari tahap vegetatif selama bagian pertama dari tiap
musim dan dominansi tahap reproduktif selama bagian
terakhir dari musim itu. Contoh dari masing-masing
kelompok seperti Tabel 7.
Memahami dengan baik perimbangan tahap vegetatif dan
reproduktif pada tanaman hortikultura sangat penting
karena karakter tanaman hortikultura sangat beragam. Pada
jenis tertentu yang bernilai ekonomi adalah buahnya tetapi
yang lainnya bisa daun, bunga, umbi atau batangnya. Dengan
mengerti perimbangan vegetatif dan reproduktif maka
tanaman yang diusahakan dapat dimanipulasi sedemikian
rupa agar memproduksi bagian yang bernilai ekonomis
seoptimal mungkin. Hal ini disebabkan karena suatu
dominansi dari tahap vegetatif mungkin diingini dalam suatu
tanaman dan suatu dominansi dari tahap reproduktif
mungkin diinginkan untuk tanaman yang lain. Sampai batasbatas tertentu perimbangan tahap e vegetatif dan reproduktif
dapat diatur melalui teknik budidaya dengan
mengoptimalkan faktor lingkungan yang mempengaruhi.
Faktor lingkungan tersebut antara lain suplai air, suhu,
suplai cahaya, dan suplai unsur hara. Karena faktor-faktor
ini biasanya membatasi pertumbuhan dan perkembangan
tanaman, bisa disebut faktor-faktor tersebut sebagai faktor
pembatas dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Pertanian sebagai sumber kehidupan manusia dalam
percakapan sehari-hari sering disebut dengan bercocok
tanam. Istilah bercocok tanam dimaksud tidak lain adalah
pengertian pertanian dalam arti sempit. Disamping
terminologi pengertian pertanian dalam arti sempit, yaitu
kegiatan bercocok tanam, terdapat pula pengertian
pertanian dalam arti luas sebagai suatu usaha untuk
mengadakan ekosistem buatan yang bertugas
menyediakan bahan makanan bagi manusia, mencakup
bidang tanaman, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
Bila ada yang bertanya kriteria apa yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu sumber kehidupan termasuk
dalam bidang pertanian?. Pertanyaan sederhana tersebut
tidaklah mudah untuk dijawab, tetapi secara umum suatu
sumber kehidupan dapat dikatagorikan sebagai bidang
pertanian apabila kegiatannya memenuhi 2 (dua) kriteria
berikut, yaitu: (1) dalam proses produksi harus terbentuk
bahan-bahan organik yang berasal dari zat-zat anorganik
dengan bantuan tumbuh-tumbuhan (berhijau daun) atau
hewan seperti ternak dan ikan, dan (2) adanya usaha untuk
memperbaharui proses produksi yang bersifat reproduktif,
pelestarian, dan/ atau budidaya. Jika hanya satu dari dua
syarat itu yang terpenuhi, maka usaha produksi tersebut
belum dapat digolongkan menjadi pertanian. Pengumpulan
bahan makanan misalnya umbi-umbian, buah-buahan, ikan,
dan hewan dari hutan, sungai atau padang rumput oleh
penduduk yang hidupnya nomaden (berpindah-pindah)
belum tergolong usaha pertanian, karena usaha reproduktif
dan budidaya belum dilakukan. Tetapi apabila pengambilan
umbi atau buah atau penangkapan ikan dari laut, sungai,
danau, atau empang yang diiringi dengan penjagaan
kelestariannya maka kegiatan tersebut dapat digolongkan
ke dalam penertian pertanian.
Menurut Kusmiadi (2014), perkembangan pertanian
dari suatu negara berjalan sesuai dengan tahapan
perkembangan masyarakat, mekanisme pasar yang berlaku,
perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, dan
perkembangan kelembagaan sosial. Proses perkembangan
pertanian pada umumnya berkaitan dengan upaya
transformasi dari sistem pertanian yang mempunyai
produktivitas rendah kepada sistem lebih modern yang
mempunyai produktivitasnya relatif tinggi dan yang
mungkin menimbulkan dampak sampingan terhadap
lingkungan akibat penggunaan teknologi dan asupan (input)
pertanian modern. Disebutkan bahwa tahapan
perkembangan pertanian berdasarkan tingkat kemajuan dan
tujuan pengelolaan sektor pertanian terdiri atas 3 tahapan,
yaitu:
1. Tahap pertama adalah pertanian tradisional yang
dicirikan dengan tingkat produktivitas sektor
pertanian yang rendah. Pada tahap ini para petani
biasanya menggarap tanah hanya sebatas yang dapat
dikelola oleh tenaga kerja keluarga tanpa memerlukan
tenaga kerja bayaran. Keadaan lingkungan statis,
penggunaan teknologi sangat terbatas, sistem
kelembagaan sosial kaku, pasar terpencar-pencar, serta
jaringan komunikasi antar daerah pedesaan danperkotaan kurang memadai dan cenderung
menghambat perkembangan produksi.
2. Tahap kedua adalah tahapan komersialisasi dari produk
pertanian mulai dilakukan, tetapi penggunaan
teknologi dan modal relatif masih rendah.
3. Tahap ketiga adalah tahap seluruh produk pertanian
ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial
dengan ciri penggunaan teknologi serta modal yang
tinggi dan mempunyai produktivitas yang tinggi pula.
Sistem pertanian (cropping system) merupakan
pengelolaan komoditas tanaman untuk memperoleh hasil
yang diinginkan yaitu berupa bahan pangan, keuntungan
finansial, kepuasan batin atau gabungan dari ketiganya.
Sistem pertanian di daerah tropika, termasuk Indonesia
berbeda dengan daerah subtropis dan daerah beriklim
sedang. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi
iklim, jenis tanaman dan keadaan sosial ekonomi petaninya.
Klasifikasi sistem pertanian (cropping system) di daerah
tropis terdapat banyak macam ,
diantaranya adalah seperti berikut.
Tingkat Efisiensi Teknologi dan Tanaman yang
Diusahakan.
Berdasarkan tingkat efisiensi teknologi dan tanaman
yang diusahakan, sistem pertanian di Indonesia dapat
dibedakan menjadi sistem ladang, sistem tegal pekarangan,
sistem sawah dan sistem perkebunan. Sistem ladang
merupakan sistem pertanian yang paling belum berkembang.
Sistem ini merupakan peralihan dari tahap pengumpul ke
tahap penanam. Pengolahan tanah minimum sekali,
produktivitas berdasarkan pada lapisan humus yang
terbentuk dari sistem hutan. Sistem ini hanya akan bertahan
di daerah yang berpenduduk jarang, dan sumber tanah tak
terbatas. Tanaman yang diusahakan umumnya tanaman
pangan, seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbiumbian. Sistem tegal pekarangan berkembang di tanah-tanah kering, yang jauh dari sumber-sumber air. Sistem ini
diusahakan setelah menetap lama, tetapi tingkatan
pengusahaan juga rendah, umumnya tenaga kurang intensif
dan tenaga hewan masih jarang digunakan. Tanamantanaman yang diusahakan terutama tanaman-tanaman yang
tahan kekeringan dan pohon-pohonan. Sistem sawah,
merupakan teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam
pengolahan tanah dan pengelolaan air, sehingga tercapai
stabilitas biologi yang tinggi dan kesuburan tanah dapat
dipertahankan. Ini dicapai dengan sistem pengairan yang
sinambung dan drainase yang lambat. Sawah merupakan
potensi besar untuk produksi pangan, baik padi maupun
palawija. Di beberapa daerah tanaman tebu dan tembakau
juga disuahakan di lahan sawah. Sedangkan sistem
perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan
besar (estate) yang dulu milik swasta asing dan sekarang
kebanyakan perusahaan negara, berkembang karena
kebutuhan tanaman ekspor seperti karet, kopi, teh dan
coklat. Dalam taraf tertentu, pengelolaa sistem perkebunan
di Indonesia merupakan yang terbaik, akan tetapi
dibandingkan dengan kemajuan di dunia berkembang hal itu
masih disarakan ketinggalan.
Sistem pertanian di daerah tropika dapat
diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu sistem pertanian
pengumpulan hasil tanaman, sistem pertanian untuk
makanan ternak dan padang penggembalaan, dan sistem
pertanian budidaya tanaman.
Sistem pertanian pengumpulan hasil tanaman adalah
sistem pertanian yang secara langsung memperoleh hasil
tanaman dari tanaman-tanaman yang tidak dibudidayakan.
Sistem ini biasanya dijalankan bersamaan dengan sistemberburu binatang dan menangkap ikan. Sistem ini di
Indonesia masih terdapat antara lain di Papua.
Penggembalaan dan Peternakan
Klasifikasi sistem pertanian untuk padang
penggembalaan dan peternakan dibuat berdasarkan tetap
tinggal (stationariness) atau tidaknya peternak dan
ternaknya dalam satu lokasi tertentu secara permanen.
Berdasarkan atar kriteria tersebut, klasifikasi sistem
pertanian dibedakan sebagai berikut:
1. Total nomadis, yaitu tidak ada tempat tinggal permanen
bagi peternaknya dan tidak ada sistem budidaya
tanaman makanan ternak teratur sehingga selalu
bergerak.
2. Semi nomadis, yaitu peternak mempunyai tempat tinggal
permanen dan di sekitarnya ada budidaya makanan
ternak sebagai tambahan, tetapi setelah waktunya lama,
ternak dan penggembalaannya bergerak ke daerahdaerah yang berbeda.
3. Transhuman, yaitu peternak mempunyai tempat tinggal
permanen, tetapi ternaknya dengan bantuan
penggembala, mengembara pada daerah penggembalaan
yang berpindah-pindah dan jauh letaknya.
4. Parsial nomadis, yaitu peternak tinggal terus menerus
pada tempat pemukiman yang tetap dan
penggembalaannya hanya pada daerah sekitarnya.
5. Peternakan menetap, yaitu peternak dan ternaknya
sepanjang tahun menetap pada lahan tertentu atau
desanya sendiri.
Sistem pertanian budidaya tanaman dapat
diklaisifikasikan lagi berdasarkan beberapa ciri-ciri spesifik
sebagai berikut:a. Berdasarkan Tipe Rotasi
Berdasarkan tipe rotasinya sistem pertanian dapat
diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu sistem pertanian
dengan rotasi bera secara alami, sistem rotasi dengan
makanan ternak (ley system), sistem dengan rotasi tegalan
(field system), dan sistem dengan rotasi tanaman tahunan.
1. Sistem pertanian dengan rotasi bera secara alami.
Sistem ini merupakan sistem dimana budidaya tanaman
dilakukan bergantian dengan bera/dikosongkan
(uncultivated fallow). Bentuk-bentuk vegetasi yang
terdapat pada sistem rotasi bera secara alami dapat
berupa yang dominan adalah pohon (forest fallow), yang
dominan adalah semak (bush fallow), yang dominan kayu
tahan api dan rumput (savanna fallow), atau yang
dominan adalah rumput (grass fallow).
2. Sistem pertanian rotasi dengan makanan ternak.
Pada sistem ini lahan ditanami tanaman-tanaman
semusim untuk beberapa tahun, setelah itu rumput
dibiarkan tumbuh atau ditanami rumput dan atau
leguminosa untuk padang penggembalaan. Dalam sistem
ini ada ley system yang diatur dan ley system alami. Pada
ley system yang diatur, tanaman semusim/pangan
dirotasikan dengan tanaman rumput dan atau
leguminosa yang dipotong untuk ternak, sedangkan pada
ley system alami, setelah tanaman semusim dipanen
rumput dibiarkan tumbuh alami untuk padang
penggembalaan ternak.
3. Sistem pertanian dengan rotasi tegalan.
Pada sistem pertanian ini tanaman semusim yang satu
ditanam setelah tanaman semusim yang lain pada lahan
tegalan/lahan kering secara bersiklus. Sebagai contoh,
pada musim hujan ditanami padi gogo kemudian setalah
itu pada musim kering ditanami jagung. Setalah panen
jagung lahan ditanami kembali dengan tanaman semusim
lain, bisa padi gogo atau yang lain, demikian seterusnya.
4. Sistem pertanian dengan rotasi tanaman tahunan
Pada sistem ini tanaman-tanaman tahunan seperti kopi,
kakao, kelapa, tebu, teh, dan karet ditanam bergantiantanaman semusim, padang penggembalaan, tanamantanaman tahunan yang lain, atau dibiarkan bera.
b. Berdasarkan Intensitas Rotasi
Dalam mengklasifikasikan sistem pertanian berdasarkan
kriteria intensitas rotasi (rotation intencity), digunakan
terminologi Intensitas Rotasi (R) dengan formula R =
jumlah tahun lahan ditanami dibagi lama siklus (dalam
tahun) dikalikan 100%. Jadi, intensitas rotasi dalam
hitungan memakai alat ukuran waktu. Sedangkan siklus
yang dimaksud adalah jumlah tahun lahan ditanami
ditambah jumlah tahun bera. Misalkan dalam siklus 10
tahun, 2 tahun lahan ditanami dan 8 tahun diberakan maka
R = 2/10 x 100 = 20%, atau dalam siklus 20 tahun, 2 tahun
lahan ditanami, 18 tahun diberakan maka R = 2/20 x 100 =
10 %. Bila lahan bera 7 tahun dan ditanami 7 tahun, maka R
= 7/14 x 100 = 50%. Berdasarkan besaran nilai R tersebut,
klasifikasi sistem pertanian dibedakan menjadi:
1. Bila R < 33%, sistem pertanian digolongkan sebagai
sistem perladangan (shifting cultivation).
2. Bila R kurang dari 60 % tetapi lebih besar dari 33%
(33<R< 66), sistem pertanian digolongkan sebagai sistem
bera (uncultivated system).
3. Bila R > 66 %, sistem pertanian digolongkan sebagai
sistem pertanian permanen (permanent cultivation).
c. Berdasarkan Intensitas Penanaman
Klasifikasi sistem pertanian berdasarkan intensitas
penanaman (cropping intencity) atau sering disingkat IP
mirip dengan klasifikasi sistem pertanian berdasarkan
intensitas rotasi (rotation intencity). Bedanya klasifikasi
berdasarkan intensitas rotasi menggunakan alat ukur
waktu, sedangkan klasifikasi berdasarkan intensitas
penanaman menggunakan alat ukur luasan lahan. Intensitas
penanaman (IP) atau cropping intencity index dihitung
dengan rumus: IP = luas areal lahan ditanami dalam setahun
(ha) dibagi dengan luas areal lahan total tersedia (ha)
dikalikan 100%. Jadi, misalkan luas areal lahan pertanian
tersedia 100 ha dan ditanami hanya satu kali dalam setahunseluas 40 ha, maka IP = 40 /100 x 100 = 40%. Tetapi apabila
luas areal lahan pertanian tersedia 100 ha, dalam satu tahun
ditanami 2 kali, pertama ditanami 100 ha dan kedua ditanami
40 ha, maka IP = 140/100 x 100 = 140%. Makin besar IP,
makin besar persentase areal lahan ditanami (ha) dibanding
dengan luas areal total (ha) tiap tahunnya. Pada pertanian
permanen, indeks penanaman (IP) lebih besar dari 66%
(sebagian besar atau seluruh lahan ditanami lebih dari satu
kali dengan sistem pola tanam ganda).
d. Berdasarkan Pola Tanam
Pola tanam (cropping pattern) adalah urut-urutan tanam
pada sebidang lahan dalam waktu satu tahun, termasuk
didalamnya masa pengolahan tanah. Klasifikasi sistem
pertanian berdasarkan pola tanam merupakan klasifikasi
sistem pertanian yang terpenting di daerah tropis. Pola
tanam di daerah tropis, biasanya disusun selama satu tahun
dengan memperhatikan curah hujan, terutama pada daerah
atau lahan yang sepernuhnya tergantung dari hujan.
Pemilihan jenis atau varietas yang ditaman perlu
disesuaikan dengan keadaan air yang tersedia ataupun curah
hujan. Contoh pola tanam : padi-padi-padi, padi-padi-bera,
padi-jagung-bera, padi-kubis-padi, dan lain-lain. Klasifikasi
sistem pertanian berdasarkan pola tanam ada 2 macam, yaitu
sistem pertanian dengan pola tanam monokultur
(monoculture) dan pola tanam polikultur (polyculture).
a. Pola tanam monokultur (sole cropping/monoculture/
sistem tanam tunggal), adalah sistem pertanian dengan
menanam hanya satu jenis tanaman saja dalam satu
periode tanam. Misalnya, sawah ditanami padi saja
(monokultur padi), jagung saja (monokultur jagung), atau
kedelai saja (monokultur jagung), dan lain-lain.
b. Pola tanam polikultur adalah sistem pertanian yang
menanm banyak jenis tanaman pada satu bidang lahan
yang terusun dan terencana dengan baik. Pola tanam
polikultur terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:
1. Tumpang sari (multiple cropping) atau disebut juga
dengan pertanaman ganda/campuran adalah salah
satu bentuk pertanaman campuran (polyculture)berupa penanaman dua jenis atau lebih tanaman
pada satu areal lahan tanam yang sama dalam waktu
yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari
yang umum dilakukan adalah penanaman dalam
waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis
tanaman budidaya yang sama, seperti jagung
dan kedelai, atau jagung dan kacang tanah.
2. Tumpang sela (intercropping) adalah tumpang sari
yang dilakukan pada pertanaman tunggal
(monokultur) suatu tanaman perkebunan besar
atau tanaman kehutanan dimana sewaktu tanaman
pokok masih kecil atau belum produktif ditanami
tanaman sela setahun seperti jagung atau kedelai,
atau tanaman dwitahun (cabai, tomat) atau bahkan
tanaman tahunan dengan habitus lebih pendek
seperti pisang.
3. Tumpang gilir (relay cropping) adalah cara bercocok
tanam dimana dalam satu areal lahan yang sama
ditanami dengan dua atau lebih jenis tanaman
dengan pengaturan waktu panen dan
tanam. Tanaman kedua ditanam menjelang panen
tanaman musim pertama. Contohnya, tumpang gilir
antara tanaman jagung yang ditanam pada awal
musim hujan dan kacang tanah yang ditanam
beberapa minggu sebelum panen jagung.
4. Pola tanam bergiliran (sequential cropping) adalah
usaha menumbuhkan dua tanaman atau lebih secara
berurutan pada tanah yang sama dalam waktu satu
tahun. Dalam sequential cropping setiap musim
tanam petani hanya mengelola satu jenis tanaman.
5. Tanaman campuran (mixed cropping), yaitu
menumbuhkan dua tanaman atau lebih secara
bersama-sama/serentak dengan tidak
memperhatikan jarak tanam atau jarak tanamnya
tidak teratur.
6. Tanaman dalam barisan (row cropping), yaitu
menanam dua tanaman atau lebih secara bersamasama/serentak dengan jarak tanam tertentu, satujenis tanaman atau lebih ditanam dalam barisan
tertentu secara teratur.
7. Pertanaman berjalur (strip cropping), yaitu
menanam dua tanaman atau lebih secara bersamasama/serentak dengan satu macam tanaman ditanam
dalam jalur-jalur tersendiri yang disusun secara
berselang-seling. Bila penanaman dilakukan di
lahan yang miring (lereng) mengikuti garis kontour
disebut dengan pertanaman “sabuk gunung” (contour
cropping).
8. Pertanaman bertingkat (multi-storey cropping), yaitu
penanaman dua jenis tanaman atau lebih berbentuk
kombinasi antara pohon dengan tanaman lain yang
berhabitus lebih pendek. Pertanaman bertingkat
yang mengkombinasikan antara pohon berupa
tanaman kehutanan dengan tanaman berhabitus
pendek berupa tanaman pertanian disebut dengan
agro-forestry.
9. Sistem surjan (alternating bed system), yaitu dua jenis
tanaman atau lebih ditanam pada sebidang lahan
yang dibentuk menjadi dua ketinggian, bagian yang
tinggi (guludan) dan yang rendah (ledokan) secara
berselang-seling. Bagian yang tinggi biasanya
berfungsi sebagai tegalan sedangkan bagian yang
rendah sebagai sawah atau untuk tanaman yang
tahan genangan.
e. Berdasarkan Suplai Air
Klasifikasi sistem pertanian berdasarkan suplai air
terdapat beberapa macam, yaitu:
1. Sistem pertanian dengan pengairan (irrigated farming)
adalah sistem pertanian dimana air dapat diatur masuk
ke lahan pertanian sesuai kebutuhan tanaman.
2. Sistem pertanian tadah hujan (rainfed farming) adalah
sistem pertanian yang pengairannya bersumber dari
curah hujan sehingga tidak bisa diatur sesuai waktu dan
kebutuhan tanaman.
3. Sistem pertanian sawah (lahan basah) (rice field
farming), yaitu sistem pertanian dibuat berteras sertadigenangi air dan ditanami padi sawah. Sistem pertanian
sawah di Indonesia ada 3 maam, yaitu:
a. Sawah irigasi, yaitu sistem pertanian dengan
pengairan yang teratur, sumber airnya dapat
diperoleh dari sungai, bendungan, waduk, atau
danau, sehingga